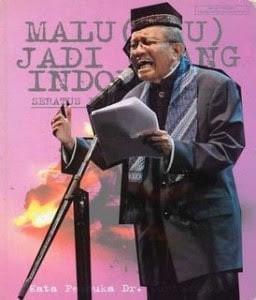Meskipun keluarganya tidak termasuk golongan bangsawan birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo sukses menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang tinggi. Cipto beserta adik-adiknya yakni Gunawan, Budiardjo, dan Syamsul Ma’bakir bersekolah di Stovia, sementara Darmawan, adiknya bahkan sukses menemukan beasiswa dari pemeintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delf, Belanda. Si bungsu, Sujitno terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta.
Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto mulai memperlihatkan perilaku yang berlawanan dari sahabat-temannya. Teman-sobat dan guru-gurunya menilai Cipto selaku pribadi yang jujur, berpikiran tajam dan tekun. “Een begaald leerling”, atau murid yang berbakat yaitu julukan yang diberikan oleh gurunya kepada Cipto. Di Stovia Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain bola sodok, Cipto lebih senang menghadiri ceramah-ceramah, baca buku dan bermain catur. Penampilannya pada acara khusus, tergolong eksentrik, dia senantiasa memakai surjan dengan materi lurik dan merokok kemenyan. Ketidakpuasan kepada lingkungan sekelilingnya, senantiasan menjadi topik pidatonya. Baginya, Stovia adalah kawasan untuk mendapatkan dirinya, dalam hal keleluasaan berpikir, lepas dari tradisi keluarga yang berpengaruh, dan berkenalan dengan lingkungan gres yang diskriminatif.
Beberapa Peraturan-peraturan di Stovia menyebabkan ketidak puasan pada dirnya, seperti semua mahasiswa Jawa dan Sumatra yang bukan Katolik diharuskan memakai busana tadisional jika sedang berada di sekolah. Bagi Cipto, peraturan berpakaian di Stovia merupakan perwujudan politik kolonial yang angkuh dan melestarikan feodalisme. Pakaian Barat cuma boleh dipakai dalam hirarki administrasi kolonial, ialah oleh pribumi yang berpangkat bupati. Masyarakat pribumi dari wedana ke bawah dan yang tidak melakukan pekerjaan pada pemerintahan, dihentikan menggunakan pakaian Barat. Implikasi dari kebiasaan ini, rakyat condong untuk tidak menghargai dan menghormati penduduk pribumi yang menggunakan pakaian tradisional.
Keadaan ini selalu digambarkannya melalui De Locomotief, pers kolonial yang sangat progresif pada waktu itu, di samping Bataviaasch Nieuwsblad. Sejak tahun 1907 Cipto telah menulis di harian De Locomotief. Tulisannya berisi kritikan, dan menentang keadaan kondisi masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Cipto sering mengkritik relasi feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Dalam tata cara feodal terjadi kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Rakyat biasanya terbatas ruang gerak dan aktivitasnya, alasannya adalah banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Keturunanlah yang menentukan nasib seseorang, bukan kemampuan atau kesanggupan. Seorang anak “biasa” akan tetap tinggal terbelakang dari anak bupati atau kaum ningrat lainnya.
Kondisi kolonial lainnya yang ditentang oleh Cipto ialah diskriminasi ras. Sebagai teladan, orang Eropa menerima honor yang lebih tinggi dari orang pribumi untuk suatu pekerjaan yang serupa. Diskriminasi menenteng perbedaan dalam banyak sekali bidang contohnya, peradilan, perbedaan pajak, keharusan kerja rodi dan kerja desa. Dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial, bangsa Indonesia menghadapi garis batas warna. Tidak semua jabatan negeri terbuka bagi bangsa Indonesia. Demikian juga dalam jual beli, bangsa Indonesia tidak mendapat peluang berjualan secara besar-besaran, tidak sembarang anak Indonesia mampu bersekolah di sekolah Eropa, tidak ada orang Indonesia yang berani masuk kamar bola dan sociteit. Semua diukur menurut warna kulit.
Tulisan-tulisannya di harian De Locomotief, menjadikan Cipto sering menerima teguran dan perayaan dari pemerintah. Untuk menjaga keleluasaan dalam berpendapat Cipto lalu keluar dari dinas pemerintah dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah duit ikatan dinasnya yang tidak sedikit.
Selain dalam bentuk goresan pena, Cipto juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus. Misalnya larangan memasuki sociteit bagi bangsa Indonesia tidak diindahkannya. Dengan pakaian khas adalah kain batik dan jas lurik, dia masuk ke sebuah sociteit yang sarat dengan orang-orang Eropa. Cipto kemudian duduk dengan kaki dijulurkan, hal itu mengundang kegaduhan di sociteit. Ketika seorang opas (penjaga) mencoba mengusir Cipto untuk keluar dari gedung, dengan lantangnya Cipto menghujat-maki sang opas serta orang-orang berada di dekatnya dengan memanfaatkan bahasa Belanda. Kewibawaan Cipto dan penggunaan bahasa Belandanya yang fasih menciptakan orang-orang Eropa terperangah.
Terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 disambut baik Cipto selaku bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jatidiri politik Cipto kian nampak. Walaupun kongres diadakan untuk memajukan perkembangan yang serasi bagi orang Jawa, tetapi pada kenyataannya terjadi keretakan antara kaum konservatif dan kaum progesif yang diwakili oleh kalangan muda. Keretakan ini sungguh ironis memulai sebuah perpecahan ideology yang terbuka bagi orang Jawa.
Dalam kongres yang pertama terjadi perpecahan antara Cipto dan Radjiman. Cipto menghendaki Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Organisasi ini harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Radjiman ingin menjadikan Budi Utomo selaku suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa.
Cipto tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi yang ia tolak ialah kebudayaan keraton yang feodalis. Cipto mengemukakan bahwa sebelum duduk perkara kebudayaan mampu dipecahan, apalagi dulu terselesaikan masalah politik. Pernyataan-pernyataan Cipto bagi jamannya dianggap radikal. Gagasan-ide Cipto menunjukkan rasionalitasnya yang tinggi, serta analisis yang tajam dengan jangkauan era depan, belum mendapat jawaban luas. Untuk membuka jalan bagi timbulnya persatuan di antara seluruh rakyat di Hindia Belanda yang mempunyai nasib sama di bawah kekuasaan abnormal, beliau tidak dapat diraih dengan mengusulkan kebangkitan kehidupan Jawa. Sumber keterbelakangan rakyat adalah penjajahan dan feodalisme.
Meskipun diangkat sebagai pengurus Budi Utomo, Cipto balasannya mengundurkan diri dari Budi Utomo yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. Sepeninggal Cipto tidak ada lagi perdebatan dalam Budi Utomo akan tetapi Budi Utomo kehilangan kekuatan progesifnya.
Setelah mengundurkan diri dari Budi Utomo, Cipto membuka praktek dokter di Solo. Meskipun demikian, Cipto tidak meninggalkan dunia politik sama sekali. Di sela-sela kesibukkannya melayani pasiennya, Cipto mendirikan Raden Ajeng Kartini Klub yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat. Perhatiannya pada politik makin menjadi-jadi setelah dia berjumpa dengan Douwes Dekker yang tengah berpropaganda untuk mendirikan Indische Partij. Cipto menyaksikan Douwes Dekker selaku mitra seperjuangan. Kerjasama dengan Douwes Dekker telah memberinya peluang untuk melakukan cita-citanya, ialah gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Bagi Cipto Indische Partij ialah upaya mulia mewakili kepentngan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak menatap suku, kelompok, dan agama.
Pada tahun 1912 Cipto pindah dari Solo ke Bandung, dengan dalih supaya akrab dengan Douwes Dekker. Ia lalu menjadi anggota redaksi penerbitan harian de Expres dan majalah het Tijdschrijft. Perkenalan antara Cipto dan Douwes Dekker yang sehaluan itu bantu-membantu sudah dijalin dikala Douwes Dekker melakukan pekerjaan pada Bataviaasch Nieuwsblad. Douwes Dekker sering berafiliasi dengan murid-murid Stovia.
Pada Nopember 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Peringatan tersebut dirayakan secara besar-besaran, juga di Hindia Belanda. Perayaan tersebut menurut Cipto selaku suatu penghinaan kepada rakyat bumi putera yang sedang dijajah. Cipto dan Suwardi Suryaningrat kemudian mendirikan suatu komite perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Dalam komite tersebut Cipto diandalkan untuk menjadi ketuanya. Komite tersebut menyiapkan akan mengumpulkan uang untuk mengirim telegram terhadap Ratu Wihelmina, yang isinya meminta semoga pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Komite Bumi Putra juga menciptakan selebaran yang bertujuan menyadarkan rakyat bahwa upacara peringatan kemerdekaan Belanda dengan mengerahkan duit dan tenaga rakyat ialah suatu penghinaan bagi bumi putera.
Aksi Komite Bumi Putera meraih puncaknya pada 19 Juli 1913, dikala harian De Express menerbitkan sebuah postingan Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Als Ik Nederlands Was” (Andaikan Saya Seorang Belanda). Pada hari berikutnya dalam harian De Express Cipto menulis postingan yang mendukung Suwardi untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Tulisan Cipto dan Suwardi sangat memukul Pemerintah Hindia Belanda, pada 30 Juli 1913 Cipto dan Suwardi dipenjarakan, pada 18 Agustus 1913 keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bareng Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker ke Belanda alasannya kegiatan propaganda anti Belanda dalam Komite Bumi Putera.

Selama masa pembuangan di Belanda, bersama Suwardi dan Douwes Dekker, Cipto tetap melancarkan aksi politiknya dengan melakukan propaganda politik menurut ideologi Indische Partij. Mereka mempublikasikan majalah De Indier yang berusaha menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan suasana di tanah jajahan. Majalah De Indier menerbitkan artikel yang menyerang budi Pemerintah Hindia Belanda.
Kehadiran tiga pemimpin tersebut di Belanda ternyata telah menjinjing dampak yang cukup bermakna kepada organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Indische Vereeniging, pada awalnya adalah perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia, sebagai tempat saling memberi berita tentang tanah airnya. Akan tetapi, kedatangan Cipto, Suwardi dan Douwes Dekker berpengaruh pada konsep-desain gres dalam gerakan organisasi ini. Konsep “Hindia bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah rakyatnya sendiri mulai dicanangkan oleh Indische Vereeniging. Pengaruh mereka semakin terasa dengan diterbitkannya jurnal Indische Vereeniging yakni Hindia Poetra pada 1916.
Oleh sebab argumentasi kesehatan, pada tahun 1914 Cipto diperbolehkan pulang kembali ke Jawa dan sejak saat itu ia bergabung dengan Insulinde, sebuah asosiasi yang menggantikan Indische Partij. Sejak itu, Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulinde untuk sementara waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulinde, terutama di daerah pesisir utara pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulinde dilakukan pula lewat majalah Indsulinde yaitu Goentoer Bergerak, lalu surat kabar berbahasa Belanda De Beweging, surat kabar Madjapahit, dan surat kabar Pahlawan. Akibat propaganda Cipto, jumlah anggota Insulinde pada tahun 1915 yang semula berjumlah 1.009 meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Insulinde meraih puncaknya pada Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Insulinde di bawah imbas berpengaruh Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda. Pada 9 Juni 1919 Insulinde mengubah nama menjadi Nationaal-Indische Partij (NIP).
Pada tahun 1918 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat). Pengangkatan anggota Volksraad dilakukan dengan dua cara. Pertama, kandidat-calon yang dipilih melalui dewan perwakilan kota, kabupaten dan propinsi. Sedangkan cara yang kedua melalui pengangkatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur jenderal Van Limburg Stirum mengangkat beberapa tokoh radikal dengan maksud biar Volksraad dapat menampung banyak sekali pemikiran sehingga sifat demokratisnya mampu ditonjolkan. Salah seorang tokoh radikal yang diangkat oleh Limburg Stirum yaitu Cipto.
Bagi Cipto pembentukan Volksraad merupakan suatu pertumbuhan yang memiliki arti, Cipto mempergunakan Volksraad selaku tempat untuk menyatakan pemikiran dan kritik terhadap pemerintah perihal masalah sosial dan politik. Meskipun Volksraad dianggap Cipto selaku sebuah pertumbuhan dalam tata cara politik, tetapi Cipto tetap menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggapnya sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi.
Pada 25 Nopember 1919 Cipto berpidato di Volksraad, yang isinya mengemukakan dilema perihal persekongkolan Sunan dan residen dalam membohongi rakyat. Cipto menyatakan bahwa santunan 12 gulden dari sunan ternyata harus dibayar rakyat dengan bekerja sedemikian usang di perkebunan yang bila dikonversi dalam duit ternyata menjadi 28 gulden.
Melihat kenyataan itu, Pemerintah Hindia Belanda menilai Cipto sebagai orang yang sungguh berbahaya, sehingga Dewan Hindia (Raad van Nederlandsch Indie) pada 15 Oktober 1920 memberi masukan terhadap Gubernur Jenderal untuk menghalau Cipto ke tempat yang tidak berbahasa Jawa. Akan namun, pada kenyataannya pembuangan Cipto ke tempat Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur masih tetap membahayakan pemerintah. Oleh alasannya itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal merekomendasikan pengusiran Cipto ke Kepulauan Timor. Pada tahun itu juga Cipto dibuang dari tempat yang berbahasa Jawa namun masih di pulau Jawa, ialah ke Bandung dan dihentikan keluar kota Bandung. Selama tinggal di Bandung, Cipto kembali membuka praktek dokter. Selama tiga tahun Cipto mengabdikan ilmu kedokterannya di Bandung, dengan sepedanya ia masuk keluar kampung untuk mengobati pasien.
Di Bandung, Cipto dapat bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda, mirip Sukarno yang pada tahun 1923 membentuk Algemeene Studie Club. Pada tahun 1927 Algemeene Studie Club diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Meskipun Cipto tidak menjadi anggota resmi dalam Algemeene Studie Club dan PNI, Cipto tetap diakui selaku penyumbang anutan bagi generasi muda. Misalnya Sukarno dalam sebuah wawancara pers pada 1959, saat ditanya siapa di antara tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang paling banyak menunjukkan efek kepada ajaran politiknya, tanpa tidak yakin Sukarno menyebut Cipto Mangunkusumo.
Pada tamat tahun 1926 dan tahun 1927 di beberapa daerah di Indo-nesia terjadi pemberontakan komunis. Pemberontakan itu menemui ke-gagalan dan ribuan orang ditangkap atau dibuang karena terlibat di dalamnya. Dalam hal ini Cipto juga ditangkap dan didakwa turut serta dalam perlawanan kepada pemerintah. Hal itu disebabkan suatu peristiwa, saat pada bulan Juli 1927 Cipto kedatangan tamu seorang militer pribumi yang berpangkat kopral dan seorang kawannya. Kepada Cipto tamu tersebut mengatakan rencananya untuk melaksanakan sabotase dengan meledakkan persediaan-persediaan mesiu, namun dia bermaksud mengunjungi keluarganya di Jatinegara, Jakarta, apalagi dulu. Untuk itu dia membutuhkan uang untuk biaya perjalanan. Cipto menasehatkan agar orang itu tidak melakukan langkah-langkah sabotase, dengan argumentasi kemanusiaan Cipto lalu menunjukkan uangnya sebesar 10 gulden kepada tamunya.
Setelah pemberontakan komunis gagal dan dibongkarnya kasus peledakan gudang mesiu di Bandung, Cipto dipanggil pemerintah untuk menghadap pengadilan sebab dianggap sudah memberikan andil dalam menolong anggota komunis dengan memberi duit 10 gulden dan diketemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukumannya Cipto kemudian dibuang ke Banda pada tahun 1928.
Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto kemudian merekomendasikan kepada pemerintah semoga Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani sebuah kontrakbahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Makasar, dan pada tahun 1940 Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Kekerasan hati Cipto untuk berpolitik dibawa sampai meninggal pada 8 Maret 1943.
Referensi :
- Balfas. 1952. Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo: Demokrat Sejati. Jakarta: Pradjaparamita.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia.
- Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: Grafitipers.
- Notosutanto Nugroho.Et al. 1977. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid V. Jakarta: balai Pustaka.
- Mulyono, Slamet. 1968. Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tashadi. 1984. Dr. D.D. Setiabudhi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
 Putera Sampoerna, mengguncang dunia bisnis Indonesia dengan menjual seluruh saham keluarganya di PT HM Sampoerna senilai Rp18,5 triliun, pada ketika kinerjanya baik. Generasi ketiga keluarga Sampoerna yang belakangan bertindak sebagai CEO Sampoerna Strategic, ini memang seorang pebisnis visioner yang bisa menjangkau pasar era depan. Berbagai langkahnya sering kali tidak terjangkau pengusaha lain sebelumnya. Dia bisa membuat sensasi (tapi terukur)dalam dunia bisnis. Sehingga pantas saja Warta Ekonomi menobatkan putra Liem Swie Ling (Aga Sampoerna) ini selaku salah seorang Tokoh Bisnis Paling Berpengaruh 2005. Sebelumnya, majalah Forbes menempatkannya dalam peringkat ke-13 Southeast Asia’s 40 Richest 2004.
Putera Sampoerna, mengguncang dunia bisnis Indonesia dengan menjual seluruh saham keluarganya di PT HM Sampoerna senilai Rp18,5 triliun, pada ketika kinerjanya baik. Generasi ketiga keluarga Sampoerna yang belakangan bertindak sebagai CEO Sampoerna Strategic, ini memang seorang pebisnis visioner yang bisa menjangkau pasar era depan. Berbagai langkahnya sering kali tidak terjangkau pengusaha lain sebelumnya. Dia bisa membuat sensasi (tapi terukur)dalam dunia bisnis. Sehingga pantas saja Warta Ekonomi menobatkan putra Liem Swie Ling (Aga Sampoerna) ini selaku salah seorang Tokoh Bisnis Paling Berpengaruh 2005. Sebelumnya, majalah Forbes menempatkannya dalam peringkat ke-13 Southeast Asia’s 40 Richest 2004.


 Taufiq Ismail lahir di Bukittinggi, 25 Juni 1935. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya, ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Yogya. Ia masuk Sekolah Menengah Pertama di Bukittinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Pada tahun 1956–1957 ia mengungguli beasiswa American Field Service Interntional School guna mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, AS, angkatan pertama dari Indonesia Ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Universitas Indonesia (kini IPB), dan selesai pada tahun1963.
Taufiq Ismail lahir di Bukittinggi, 25 Juni 1935. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya, ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Yogya. Ia masuk Sekolah Menengah Pertama di Bukittinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Pada tahun 1956–1957 ia mengungguli beasiswa American Field Service Interntional School guna mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, AS, angkatan pertama dari Indonesia Ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Universitas Indonesia (kini IPB), dan selesai pada tahun1963.