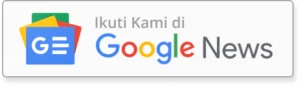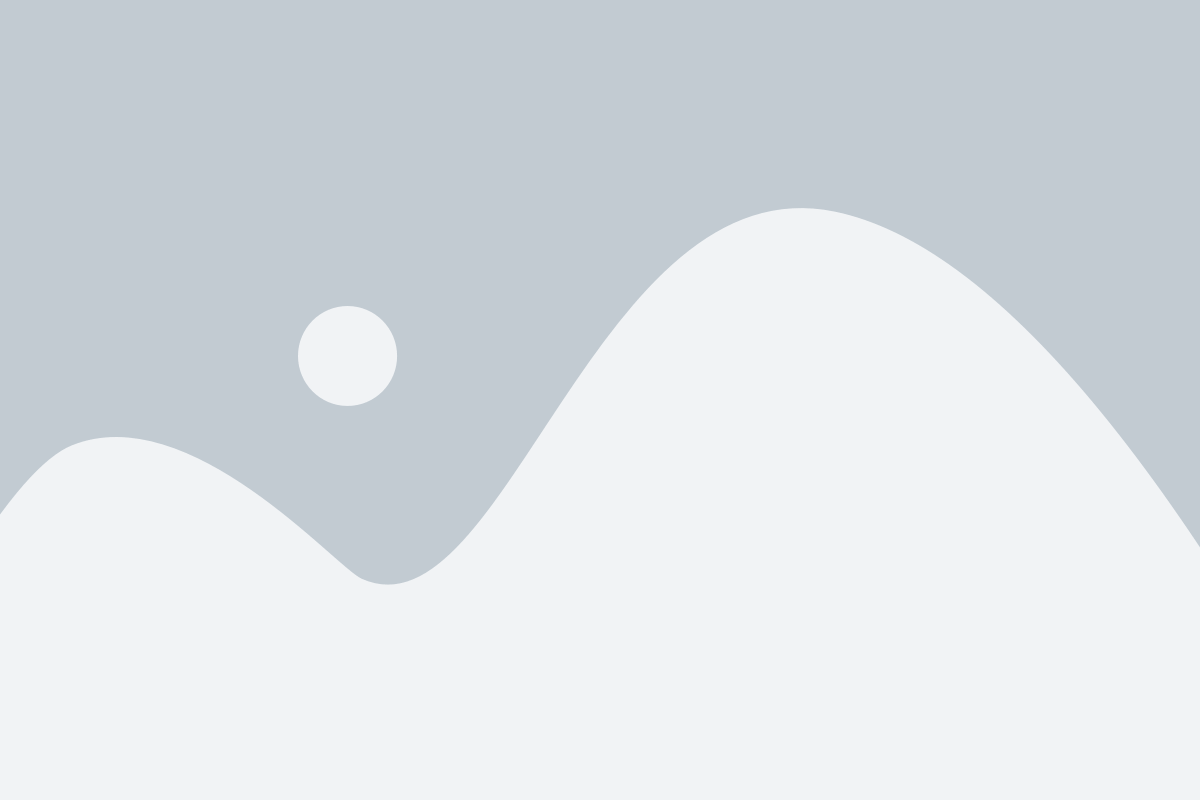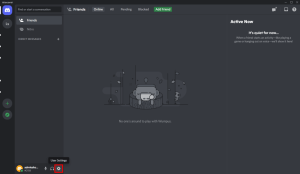Biografi PK Ojong. Nama lengkapnya Petrus Kanisius Ojong atau Auwjong Peng Koen Lahir di Bukittinggi, 25 Juli 1920, dengan nama Auw Jong Peng Koen ia adalah salah satu pendiri surat kabar Kompas selain Jakob Oetama. Ayahnya, Auw Jong Pauw, sejak dini giat membisikkan kata ekonomis, disiplin, dan tekun kepadanya. Auw Jong Pauw awalnya petani di Pulau Quemoy (sekarang kawasan Taiwan) yang lalu merantau ke Sumatra Barat. Ojong sudah dikaruniai anugerah tak terkira. Kelak, meski sudah menjadi juragan tembakau, trilogi ekonomis, disiplin, dan bersungguh-sungguh tetap dipedomani keluarga besar (11 anak dari dua istri; istri pertama Jong Pauw meninggal sehabis melahirkan anak ke-7. Peng Koen anak sulung dari istri kedua) yang menetap di Payakumbuh ini. Saat Peng Koen kecil, jumlah kendaraan beroda empat di Payakumbuh tak sampai sepuluh, salah satunya milik ayahnya. Artinya, mereka hidup berkecukupan.
Biografi PK Ojong. Nama lengkapnya Petrus Kanisius Ojong atau Auwjong Peng Koen Lahir di Bukittinggi, 25 Juli 1920, dengan nama Auw Jong Peng Koen ia adalah salah satu pendiri surat kabar Kompas selain Jakob Oetama. Ayahnya, Auw Jong Pauw, sejak dini giat membisikkan kata ekonomis, disiplin, dan tekun kepadanya. Auw Jong Pauw awalnya petani di Pulau Quemoy (sekarang kawasan Taiwan) yang lalu merantau ke Sumatra Barat. Ojong sudah dikaruniai anugerah tak terkira. Kelak, meski sudah menjadi juragan tembakau, trilogi ekonomis, disiplin, dan bersungguh-sungguh tetap dipedomani keluarga besar (11 anak dari dua istri; istri pertama Jong Pauw meninggal sehabis melahirkan anak ke-7. Peng Koen anak sulung dari istri kedua) yang menetap di Payakumbuh ini. Saat Peng Koen kecil, jumlah kendaraan beroda empat di Payakumbuh tak sampai sepuluh, salah satunya milik ayahnya. Artinya, mereka hidup berkecukupan.
Tapi, Sang Ayah, Jong Pauw selalu berpesan, nasi di piring harus dihabiskan sampai butir terakhir. Sampai kematian, Peng Koen tak pernah menyentong nasi lebih dari yang kira-kira mampu dihabiskan. Ojong memiliki enam anak, empat di antaranya laki-laki. P.K. Ojong saat bersekolah di Hollandsch Chineesche School (HCS, sekolah dasar khusus warga Tionghoa) Payakumbuh. Di periode ini, beliau berkenalan dengan aliran agama Kristen. Beberapa waktu kemudian, ia masuk Kristen dan mendapat nama baptis Andreas. Ia gemar membaca koran dan majalah yang dilanggani asosiasi penghuni asrama. Kalau murid lain hanya memperhatikan isi tajuk planning, Auwjong menelaah juga cara penulisan dan penyajian gagasan. Sifat-sifat itu membentuk aksara Auwjong. Kebiasaan hemat membuatnya hati-hati dan teliti. Disiplin dan rajin membentuk ia jadi orang yang lurus dan serius.
Walau semenjak di HCK Meester Cornelis ia telah mulai menulis, pekerjaan pertama Auwjong adalah guru. Mudah dimengerti alasannya HCK memang sekolah calon guru. Dia menentukan HCK alasannya ongkosnya murah. Kebetulan, keadaan keuangan keluarganya sepeninggal sang ayah tahun 1933 tidak terlalu baik.Selulus HCK pada Agustus 1940, dia mengajar di kelas I Hollandsch Chineesche Broederschool St. Johannes di daerah Jakarta Kota. Saat Jepang menyerbu Hindia Belanda, sekolah-sekolah ditutup. Seperti guru-guru lain, Auwjong kehilangan mata pencaharian. Tamatlah kariernya di bidang pendidikan. Waktu bergulir, Auwjong kian lihai memainkan pena. Kepercayaan besar datang, menyusul pengangkatannya selaku redaktur pelaksana Star Weekly. Di tengah aktivitas mencari gosip, dia menyempatkan diri menimba ilmu di Rechts Hoge School (RHS), sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dia juga aktif membantu kegiatan berbau sosial yang diadakan Sin Ming Hui (sekarang Candra Naya), asosiasi sosial yang diresmikan Khoe Woen Sioe dan Injo Beng Goat. Sin Ming Hui didirikan untuk menyalurkan kekecewaan mereka pada para pemuka Tionghoa yang bau tanah-tua dan kaya-raya. Khoe dan Injo merasa para pemuka itu tidak membela orang-orang yang diwakilinya. Khoe dan Injo dikenal sebagai duo antikomunis. Injo Beng Goat bahkan pernah berpidato di corong RRI, merekomendasikan kelompok Tionghoa senantiasa mendukung RI. Kelak, Sin Ming Hui menjadi pelopor lahirnya sejumlah organisasi sosial, di antaranya RS Sumber Waras dan Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Tahun 1951, Auwjong lulus RHS. Ia secepatnya diangkat menjadi pemimpin redaksi Star Weekly. Ia meminta para mahir menulis wacana problem yang hangat. Saat Amerika meledakkan bom hidrogen, contohnya, Auwjong mencari orang yang mampu menjelaskan secara terkenal terhadap pembaca. Agar ceritanya tidak terlampau ilmiah, ia menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang umum timbul di benak awam, kemudian menerjemahkan keterangan rumit si jago tadi. Auwjong sangat jago dalam soal seperti ini. Sebagai pengasuh rubrik tetap, dipilih mereka yang benar-benar andal. Umpamanya, ruang pajak diasuh Mr. Sindian Djajadiningrat, Direktur Jenderal Iuran Negara dikala itu. Sedangkan Prof. Poorwo Soedarmo, dokter andal gizi yang memperkenalkan rancangan “Empat Sehat Lima Sempurna”, mengasuh ruang gizi.
Auwjong tergolong kutu buku. Buku hariannya penuh judul buku, tanggal, dan harga pembeliannya. Bahkan, selama perjalanan berangkat atau pulang kantor pun dia memelototi bacaan. Dari koleksi bukunya, tercermin luasnya minat Auwjong. Mulai yang berbau hukum, sejarah, kesenian, kesusasteraan, kebudayaan, sosiologi, sains, jurnalistik, filsafat, kisah kriminal, psikologi, tumbuhan, kesehatan, hingga buku kuliner. Cerita wacana Perang Eropa dan Pasifik yang dimuat Star Weekly tahun 1950-an ialah buah kesukaan Auwjong membaca. Sebagai pimpinan majalah yang cukup disegani, Auwjong tak mampu menutup mata dari aktivitas berbau politik. Akhir 1953, beliau tergolong orang yang prihatin pada nasib kalangan Tionghoa peranakan yang terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.
Waktu itu, pemerintah membuat RUU yang menganggap peranakan Tionghoa di Indonesia memiliki kewarganegaraan rangkap. Kalau mau menjadi WNI, mereka harus aktif menolak kewarganegaraan RRC. Aturan ini sangat tidak menguntungkan buat peranakan Tionghoa yang tinggal di pelosok dan tidak pandai. Puncaknya, dalam pertemuan di Gedung Sin Ming Hui, berkumpul sejumlah tokoh peranakan Tionghoa, di antaranya Siauw Giok Tjhan, Tan Po Goan, Tjoeng Tin Jan, Tjoa Sie Hwie (keempatnya angota dewan legislatif), Yap Thiam Hien, Oei Tjoe Tat. Mereka membentuk panitia yang bertugas meneliti problem kewarganegaraan Indonesia bagi keturunan Tionghoa dengan Siauw Giok Tjhan, (anggota dewan legislatif) menjadi ketua. Panitia ini juga melahirkan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Bersama sembilan tokoh peranakan Tionghoa lainnya (di antaranya Injo Beng Goat dan Onghokham) beliau menandatangani pernyataan berisi dukungan terhadap proses asimilasi, namun mengimbau agar prosesnya berlangsung tanpa paksaan.
Pada dikala bersamaan, isi Star Weekly makin menasional. Kalau tadinya edisi khusus hanya untuk menyambut Tahun Baru Imlek, maka kemudian ada edisi Idul Fitri, 17 Agustus, bahkan hari Kebangkitan Nasional. Sampai tahun 1958, tirasnya sudah 52.000; angka yang mengesankan. Itu berkebalikan dengan nasib Keng Po. Pada 1 Agustus 1957, surat kabar antikomunis itu diberangus pemerintah tanpa argumentasi terang. Namun bisa diduga, pembredelan ini tak lepas dari peran PKI yang ketika itu besar pengaruhnya di pemerintahan. PT Keng Po mengubah nama menjadi PT Kinta (singkatan dari kertas dan tinta).
Itu sebabnya, Auwjong jadi kian hati-hati. Rubrik “Gambang Kromong” yang berisi sentilan dihilangkan. Sedangkan “Timbangan” berubah nama menjadi “Intisari”. Benar, Star Weekly tak luput dari peringatan. Rubrik “Tinjauan Luar Negeri”, misalnya, kerap dianggap menyentil kebijakan luar negeri Indonesia. Puncaknya, Auwjong diundang pihak yang berwenang. Satu kalimat yang ia ucapkan sekembali dari sana adalah, “Wij zijn dood, “Kita semua mati”. Seisi kantor bengong. Pemerintah tak pernah menyebut dengan terang argumentasi penutupan majalah bertiras 60.000 (sampai nomor terakhir, 7 Oktober 1961) itu.
Meski dibredel, Auwjong dan para karyawan tetap masuk seperti biasa. Khoe Woen Sioe, administrator Keng Po dan pimpinan Star Weekly berupaya menyalurkan mereka ke unit perjuangan lain. Khoe sadar, kepandaian sebagian besar anak buahnya cuma tulis-menulis dan cetak-mencetak. Maka, didirikanlah PT Saka Widya yang menerbitkan buku-buku. Sejak itu, Auwjong punya jabatan baru, eksekutif perusahaan penerbitan buku.
LAHIRNYA “INTISARI” DAN “KOMPAS”
Saat PT Kinta dilanda kemunduran tahun 1963, Auwjong dan Jakob Oetama mempublikasikan majalah yang diniatkan untuk membebaskan penduduk dari keterkucilan berita. sejak awal 1960-an, Auwjong dan Jakob keduanya sama-sama menjadi pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Juga pernah sama-sama jadi guru dan punya minat besar pada sejarah. Seperti Star Weekly, Intisari melibatkan banyak jago. Di antaranya jago ekonomi Prof. Widjojo Nitisastro, penulis duduk perkara-duduk perkara ekonomi terkenal Drs. Sanjoto Sastromihardjo, atau sejarawan muda Nugroho Notosusanto. Saat itu, pergaulan Auwjong telah sungguh luas. Dia berteman baik dengan Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Soe Hok Gie, dan Machfudi Mangkudilaga. Intisari terbit 17 Agustus 1963. Seperti Star Weekly, ia hitam-putih dan telanjang, tanpa kulit muka. Ukurannya 14 X 17,5 cm, dengan tebal 128 halaman. Logo “Intisari”-nya sama dengan logo rubrik senama yang diasuh Ojong di Star Weekly. Edisi perdana yang dicetak 10.000 eksemplar ternyata laku manis.
Kira-kira dua tahun umur Intisari, Ojong dan Jakob menerbitkan Harian Kompas. Saat itu, kekerabatan antara Intisari dan Kompas mirip-mirip Star Weekly dan Keng Po. Saling membantu, berkantor sama, bahkan wartawannya pun merangkap. Setelah beberapa pengurus Yayasan Bentara Rakyat bertemu Bung Karno, beliau merekomendasikan nama “Kompas”. Pengurus yayasan – I.J. Kasimo (Ketua), Frans Seda (Wakil Ketua), F.C. Palaunsuka (Penulis I), Jakob Oetama (Penulis II), dan Auwjong Peng Koen (bendahara) – baiklah. Mereka juga menyetujui sifat harian yang independen, menggali sumber isu sendiri, serta mengimbangi secara aktif imbas komunis, dengan tetap berpegang pada kebenaran, kecermatan sesuai profesi, dan budpekerti pemberitaan. Sesuai sifat Auwjong yang selalu merencanakan segala sesuatunya dengan teliti, kelahiran Kompas disiapkan sematang mungkin.
Soalnya, modal awal mereka hanya Rp 100.000,-, sebagian uang Intisari. Maka, 28 Juni 1965 terbit Kompas nomor percobaan yang pertama. Setelah tiga hari berturut-turut berlabel percobaan, barulah Kompas yang bantu-membantu beredar. Seperti di Intisari, karena argumentasi politis, nama Auwjong tak dicantumkan di jajaran redaksi. Intisari dan Kompas membuat Ojong bersemangat. Pagi-pagi, sebelum pukul 06.30, beliau telah menjemput para karyawan dengan Opel Caravan. Di perjalanan, Auwjong umummengajak mereka mengobrol. Pukul 07.00 Ojong sudah di kantor. “Jangan tiba pukul sembilan, jika ingin karyawan datang pukul tujuh,” cetusnya. Tapi Kompas sendiri mulanya sering telat terbit sampai dijuluki komt pas morgen (besok gres datang). Ketika terjadi kejadian G30S/PKI, Ojong dan Jakob mesti mengambil keputusan di dikala paling krusial. Pelaku kudeta baru mengeluarkan ketentuan, setiap koran yang terbit mesti menyatakan kesetiaan. “Jakob, kita tidak akan melakukannya. Sama saja ditutup sekarang dan mungkin juga menderita kini atau beberapa hari lagi,” tegas Ojong.
Pilihan ini terbukti benar karena upaya PKI gagal total. Tanggal 6 Oktober, semua koran yang tak pernah menyatakan setia pada upaya kup boleh terbit kembali. Keruan saja, dalam keadaan langka koran, Kompas mulai dilirik. Beberapa hari kemudian, saat koran-koran mapan terbit kembali, banyak pembaca tetap membeli Kompas, alasannya telanjur mengasihi surat kabar yang gres mereka kenal ini. Ojong tidak pernah berambisi membuat korannya bertiras paling tinggi. “Biar orang lain saja yang oplahnya terbesar. Kita menjadi nomor dua paling besar saja,” katanya. Menjelang ajal, Ojong mulai sadar cara kerja orang lain tak mesti sama dengannya. Tak siapa saja bisa bekerja seharian tanpa berhenti sebentar pada ketika-ketika tertentu untuk beroleh kesejukan baru. Tak heran, kematiannya 31 Mei 1980 terasa begitu “mudah”. Begitu secara tiba-tiba, tanpa didahului sakit yang menyiksa. Barangkali memang hanya wartawan “lurus” yang bisa begini, meninggal dengan benda kesayangan (buku) di sampingnya. www.biografiku.com